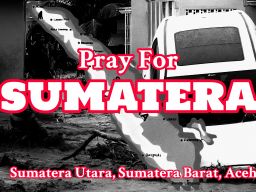Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera :
"Hutan Dirusak, Rakyat Jadi Korban, Siklus Brutal Kebijakan Lingkungan"
Oleh : Abdul Rasyid
Jum'at, 28 November 2025
Baca Juga: Framing Jahat Xpose Uncensored Trans7 Terhadap KH. Anwar Manshur dan Krisis Etika Jurnalistik
Banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh, bedasarkan Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan beberapa sumber data sebagai berikut :
Provinsi Sumatera Utara, sebagai informasi, berdasarkan data pada Kamis, 27 November 2025, terdapat 10 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor. Di antaranya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Langkat, Padang Sidimpuan, dan Nias Selatan. Dilaporkan sebanyak total 30 jiwa meninggal dunia di Sumut. Serta ada kurang lebih 4.035 warga yang mengungsi.
Provinsi Sumatera Barat, pada Kamis, 27 November 2025, terdapat 13 kabupaten/kota berstatus tanggap darurat bencana, yang sangat parah itu Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kabupetan Agam, itu yang paling berat. Belasan korban jiwa, di Agam ada 5 orang dalam pencarian, kemungkinan korban jiwa bertambah, Korban luka-luka diperkirakan ratusan jiwa. Fasilitas umum dan akses jalan: masuk dan keluar Kota Padang, dari empat jalur, tiga jalur mengalami gangguan, yaitu Padang-Solok, Padang-Bukitiinggi, Padang-Malalak. Hingga Jumat (28/11/2025) pagi, jumlah korban banjir bandang di Malalak, Agam, Sumatera Barat, telah mencapai sembilan orang.
Provinsi Aceh, Hingga Jum'at hari ini 28 November 2025, menurut Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, sampai saat ini total membuat 119.998 jiwa terdampak dan 20.759 orang mengungsi. Sementara 30 orang meninggal dunia dan 16 masih hilang. Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) bencana banjir kini menerjang 16 kabupaten/kota. Masing-masing di Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara dan Aceh Selatan.
Banjir dan tanah longsor kembali mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya negara yang “rawan bencana”, akan tetapi Indonesia adalah negara yang membiarkan dirinya terus-menerus dibanjiri bencana akibat kelalaian struktural.
Bencana ini bukan sekadar hujan ekstrem, tetapi akumulasi dari deforestasi, pertambangan tak terkendali, pembukaan lahan massif, dan pengawasan negara yang melemah (KLHK, 2023).
Pada titik ini, publik perlu memahami, bahwa
Hujan tidak menebang pohon; manusia yang melakukannya. Hutan tidak merusak dirinya sendiri; kebijakan salah arah yang melakukannya. Dan bencana yang terjadi bukan cuma lumpur yang turun dari bukit, melainkan mandat negara yang ikut runtuh.
Hutan Rusak, Air Mengamuk, Bukti Ilmiah Tidak Bisa Dibantah
Berbagai penelitian ilmiah sudah lama menyimpulkan bahwa deforestasi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor secara signifikan.
Kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa 92% kejadian banjir dan longsor di Indonesia terjadi di area dengan tingkat degradasi hutan tinggi (BNPB, 2022).
Temuan serupa juga disampaikan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) Organisasi Pangan dan Pertanian (2021) :
1. Hilangnya tutupan pohon menyebabkan infiltrasi air turun hingga 70%.
2. Run-off permukaan meningkat hingga 5 kali lipat.
3. Material tanah lebih mudah terlepas dari struktur lereng yang tak lagi diperkuat akar pohon.
Di daerah hulu Sumatera, termasuk kawasan sekitar Sibolga, Padang, dan Aceh, citra satelit Global Forest Watch menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta hektare hutan hilang dalam rentang 2001–2023, sebagian besar akibat ekspansi tambang dan perkebunan.
Dengan bukti ilmiah tersebut, menyalahkan hujan, banjir, tanah longsor adalah narasi yang absurd. Sama absurdnya seperti menyalahkan angin ketika rumah kita roboh, karena kita sendiri yang mencabut semua pilar penyangganya.
Perizinan Bukan Kekebalan Hukum
Bencana ekologis yang terjadi di Sumatera adalah bukti bahwa kerusakan lingkungan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan akibat keputusan perizinan yang memberikan akses pada perusahaan pertambangan, korporasi kayu, dan pelaku bisnis pembukaan lahan. Secara hukum, izin bukanlah pembenaran untuk merusak.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menegaskan bahwa :
1. Setiap kegiatan wajib mencegah kerusakan lingkungan (Pasal 2 dan Pasal 15),
2. Izin lingkungan dapat dicabut apabila menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan (Pasal 76),
3. Pemerintah bertanggung jawab mengawasi, menegakkan hukum, dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 65).
Dengan demikian, kerusakan hutan adalah kegagalan penegakan hukum, bukan semata-mata ketidakpedulian alam.
UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) juga menegaskan bahwa kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan daerah resapan air tidak boleh dialihfungsikan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa di banyak kawasan Sumatera, izin justru diberikan di area yang secara geologis dan ekologis berbahaya.
Jika negara memberikan izin di kawasan yang seharusnya dilindungi, maka negara ikut menandatangani kontrak bencana itu sendiri.
Bencana Mengungkap Fakta Kegagalan Politik Tata Ruang
Indonesia sesungguhnya memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melindungi kawasan rawan bencana, terutama melalui :
1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
3. UU PPLH 32/2009,
4. UU Kehutanan 41/1999.
Akan tetapi, seperti yang sering disampaikan para ahli tata ruang, “Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tetapi pada diskresi yang berlebihan dan pengawasan yang minim.”
Hasil penelitian WALHI (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 35% izin usaha tambang di Pulau Sumatera berada di kawasan yang dikategorikan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) tingkat sedang hingga tinggi.
Baca Juga: Ilmu Akademik, Skill, dan Peradaban Digital : Menjawab Tantangan Zaman
Hal tersebut berarti bukan hanya pembangunan yang keliru, tetapi tata ruang itu sendiri disusun tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis, fakta adanya pelanggaran langsung pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Penataan Ruang.
Paradoks Negara, Menjaga Lingkungan di Atas Kertas, Merusaknya di Lapangan
Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban :
1. Melindungi hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1 UUD 1945),
2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945).
Dua mandat ini tidak boleh dipisahkan.
Namun dalam praktiknya, negara sering terjebak pada paradoks kebijakan :
1. Di satu sisi, menerbitkan aturan ketat atas perlindungan lingkungan.
2. Di sisi lain, terus mendorong ekspansi pertambangan, perkebunan, dan pembangunan yang menggerus kawasan lindung.
Ketika kepentingan ekonomi jangka pendek mendominasi, prinsip keberlanjutan (sustainability) terdegradasi menjadi jargon.
Padahal Fernando et al. (2020) menegaskan bahwa negara hanya dapat dianggap menjalankan kewajiban konstitusionalnya, apabila melaksanakan prinsip due diligence, yaitu; tindakan kehati-hatian, pencegahan, dan pengawasan aktif terhadap setiap potensi kerusakan lingkungan.
Kehadiran Negara Tidak Cukup Hanya Saat Terjadi Bencana
Setiap kali bencana terjadi, negara hadir di depan kamera : meninjau lokasi, mengirim bantuan, memberikan pernyataan belasungkawa, yang absen adalah kehadiran sebelum bencana, yaitu dalam bentuk:
1. Penegakan hukum atas pembalakan liar,
2. Audit lingkungan pada perusahaan tambang,
3. Evaluasi izin usaha,
4. Penataan ulang kawasan hutan lindung,
5. Pengawasan ketat terhadap daerah tangkapan air dan sempadan sungai.
Dalam perspektif hukum lingkungan, negara dianggap lalai apabila:
1. Mengabaikan peringatan ilmiah,
2. Memberikan izin di kawasan rawan,
3. Gagal melakukan pengawasan,
4. Tidak mencabut izin yang bermasalah,
5. Tidak menindak pelanggaran dan pembalakan liar.
Banjir bandang di Sumatera adalah cermin dari kelalaian negara.
Sudah saatnya media, pemerintah, dan masyarakat berhenti menyebut bencana ekologis sebagai “musibah” belaka.
Banjir dan longsor bukan musibah, tetapi akibat dari:
1. Hilangnya hutan,
2. Rakusnya eksploitasi tambang,
3. Tata ruang yang korup,
4. Izin yang longsor sebelum tanahnya longsor.
Dengan menempatkan bencana sebagai “musibah”, publik kehilangan kesempatan untuk melihatnya sebagai kegagalan tata kelola lingkungan.
Apa yang Harus Dilakukan Negara
Baca Juga: Ilmu Akademik, Skill, dan Peradaban Digital : Menjawab Tantangan Zaman
1. Moratorium Izin Tambang dan Pembukaan Lahan di KRB
Kawasan hulu, pegunungan, dan daerah resapan harus dibekukan dari seluruh aktivitas ekstraktif.
2. Audit Lingkungan Menyeluruh
Instrumen AMDAL harus menjadi dokumen ilmiah, bukan formalitas administrasi.
Audit harus melibatkan perguruan tinggi dan lembaga independen (lihat UU PPLH Pasal 63).
3. Pengawasan Ekstra Ketat
UU PPLH memberi wewenang kepada pemerintah untuk membekukan bahkan mencabut izin tanpa menunggu proses pidana.
4. Penegakan Hukum Korporasi
Pasal 116–119 UU PPLH membuka kemungkinan pengenaan pidana korporasi, termasuk pertanggungjawaban direksi.
5. Rekonstruksi Tata Ruang dengan Prinsip Ekologi
Penataan ruang harus berbasis risiko bencana dan daya dukung lingkungan, bukan tekanan investasi.
Dalam dunia hukum lingkungan, mencegah satu pohon ditebang ilegal lebih berharga daripada 100 konferensi pasca-bencana.
Bencana yang terjadi hari ini adalah peringatan, bukan untuk alam, tetapi untuk negara.
Banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera; Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh bukanlah sekadar gejala alam, tetapi gejala negara sedang kehilangan kompas ekologisnya.
Jika pemerintah terus memandang bencana ekologis sebagai “takdir alam”, wilayah Sumatera akan terus berduka, karena akar persoalannya bukan cuaca, melainkan cara memperlakukan alam.
Hutan yang ditebang hari ini mungkin menghasilkan keuntungan bagi segelintir orang, tetapi pada akhirnya akan merenggut sesuatu yang jauh lebih besar, yakni; keseimbangan lingkungan yang selama ini melindungi warga masyarakat, flora dan fauna.
Banjir dan tanah longsor yang menewaskan warga adalah bukti nyata bahwa kita sedang menuai hasil dari kebijakan yang salah arah. Dan jika negara tidak segera mengubah arah kebijakan, tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu.
Sumatera berduka, tetapi duka ini bukan akhir, bencana ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa menjaga hutan bukan hanya soal keindahan alam, melainkan soal menjaga keseimbangan alam dan lingkungan demi keberlangsungan kehidupan.
Penulis : Abdul Rasyid - Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Editor : Redaktur